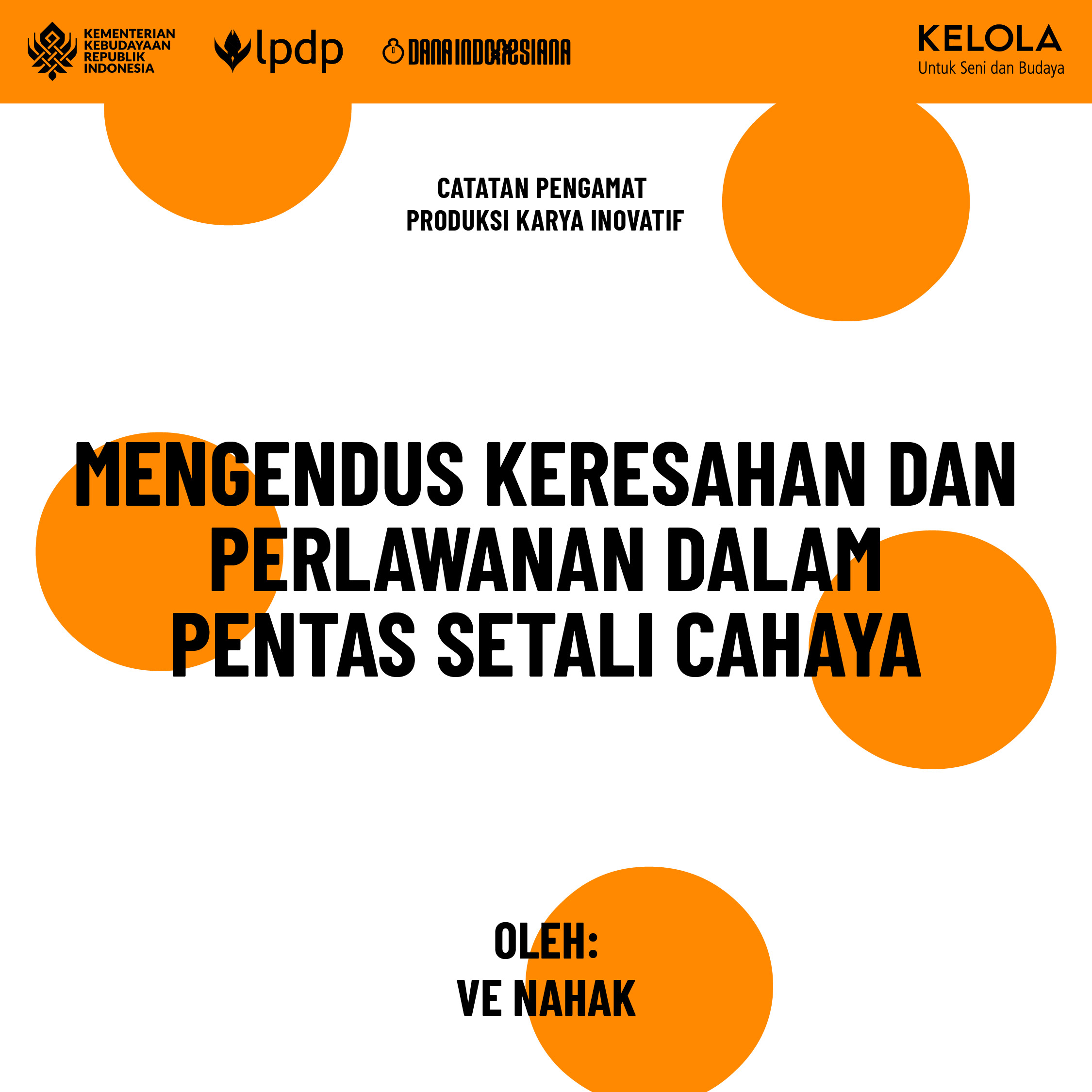Oleh Ve Nahak
Catatan Pengamat untuk pertunjukan “Setali Cahaya” karya Wulan Saraswati & Rio Nuwa, yang merupakan bagian dari Produksi Karya Inovatif
Lampu padam ketika kami diarahkan ke ruang pentas. Dari arah penonton, tampak layar lebar berukuran 8 x 10 meter menayangkan gulungan ombak di tepi pantai. Suara hempasannya sahut-menyahut; mengingatkanku pada musim barat di Flores, antara Desember-Februari. Angin kencang, ombak menghantam pantai berkali-kali.
Gelora laut masih menderu dari pengeras suara ketika empat pelakon masuk pentas. Seorang yang di depan berdiri, sedangkan yang di belakang menunduk sambil memegang pinggang temannya. Pasangan Intan-Angga dan Sylvi-Mags mengayunkan kaki dengan hati-hati ibarat langkah orang yang menjinjit agar tidak berisik. Mereka bergerak perlahan mengitari panggung, melawan arah jarum jam. Sorot cahaya memantulkan siluet di dinding: dua sosok centaur – kuda berkepala manusia – berjalan di tepi pantai. Sesudah tiga putaran, deru laut melemah. Gee masuk panggung dari sisi kiri dan membacakan puisi Pada Sebuah Pantai: Interlude karya Goenawan Mohamad.
 Gambar 1. Dua sosok centaur berjalan pelan mengitari panggung (Dok. pribadi Ve Nahak)
Gambar 1. Dua sosok centaur berjalan pelan mengitari panggung (Dok. pribadi Ve Nahak)
Rekaman hempasan gelombang dan puisi GM menggarisbawahi kata kunci pertama dari judul pertunjukan malam itu: “Pantai”.
Selain menambah suasana meditatif, kehadiran centaur merupakan strategi yang baik untuk tidak membiarkan panggung terlalu lengang. Walaupun demikian, dua sosok ini masih menyisakan teka-teki bagiku.
Kebencian absurd
Misteri dua sosok itu baru terjawab dalam penggalan-penggalan kisah dua sahabat yang tampil di fragmen pertama, berjudul “Pantai dan Perihal yang Tak Sempat Kita Bicarakan”. Judul kecil dalam surat undangan yang beredar ternyata berasal dari judul fragmen ini.
Lampu menyorot dua anak muda di sisi kanan panggung. Mereka memperkenalkan diri; Intan dari Maumere dan Angga dari Bali. Keduanya secara bergantian berkisah tentang pengalaman masa kecil tentang pantai. Mereka seperti sedang menjawab satu daftar pertanyaan.
 Gambar 2. Indan dan Angga di pojok kanan berkisah tentang pengalaman masa kecil mereka tentang pantai (Dok. pribadi Ve Nahak)
Gambar 2. Indan dan Angga di pojok kanan berkisah tentang pengalaman masa kecil mereka tentang pantai (Dok. pribadi Ve Nahak)
Sebagai penonton saya mudah mengikuti percakapan mereka. Topiknya dimulai dari soal remeh-temeh; berapa jarak rumah ke pantai?, apakah kamu suka laut?, apakah kamu suka piknik?, kapan terakhir kali piknik ke pantai? bersama siapa dan dalam rangka apa?, kendaraan apa yang biasa digunakan untuk ke tempat piknik? Milik sendiri atau disewa?, dan seterusnya.
Jawaban Intan dan Angga menyingkap perbedaan di antara mereka. Bagi Intan, piknik adalah urusan komunal. Piknik melibatkan tetangga dan biasanya dilakukan secara bersama sebagai cara mempererat kohesi sosial di antara tetangga. Sebaliknya, bagi Angga, piknik adalah urusan privat, entah satu orang atau paling-paling satu keluarga. Tentu sulit untuk menyimpulkan, apakah ini mencerminkan budaya komunal masyarakat Flores di satu sisi dan budaya individu yang makin kental di Bali akibat turisme?
Kenangan dua anak muda generasi Z itu tentang pantai dan piknik, menurut hemat saya, mudah terhubung dengan para penonton. Memori kolektif sekitar seratus orang yang mengisi rujab Bupati Sikka pada malam Minggu 12 Juli 2025 pasti beriirisan cukup tebal dengan pengalaman Intan, si gadis Maumere. Urusan piknik adalah urusan satu RT atau bahkan urusan satu kampung. Di sini, pengalaman Angga menjadi penting untuk memberi kontras pada cara orang-orang Maumere menghayati piknik.
Budaya komunal orang Maumere mengalami disrupsi ketika pantai mulai dikelola dengan logika yang berbeda. “Dulu tempat piknik andalan kami adalah pantai Paris di Lokaria. Tapi kini telah tiada. Karena itu kami pindah ke pantai Krokowolon. Katanya itu pantai milik gereja. Ada juga pantai Pintar Asia, pantai milik koperasi kaya di Maumere,” kata Intan.
Intan mencatat pergeseran tata kelola pantai di Maumere dalam dua puluh tahun terakhir ini. “Kalau dulu di pantai Paris, siapapun bisa masuk tanpa harus bayar. Tapi sekarang pantai Paris sudah tak ada. Sudah dibangun hotel dan kafe-kafe. Sementara pantai-pantai lain sudah berbayar. Karcis masuk, listrik, semuanya berbayar.”
Pantai yang dulunya terbuka untuk umum kini perlahan-lahan ditata menjadi ekslusif. Karcis masuk, listrik dan sewa tempat memperkuat imajinasi tentang kemewahan dari sebuah peristiwa yang disebut “piknik”. Padahal, dulu pantai merupakan bagian dari kosa kata dan tutur lisan masyarakat Sikka. Pantai diucapkan oleh semua orang tanpa beban finansial di baliknya.
Lantaran konsep pertunjukan ini berupa sharing pengalaman personal tentang pantai, isu krusial yang hendak diangkat tidak dielaborasi lebih dalam. Penonton mendapat kisah-kisah yang fragmentaris. Suara Intan di panggung boleh dikatakan mewakili keluhan-keluhan warga kebanyakan yang sering luput dari headline media massa lokal. Rupanya pertunjukan ini tidak dirancang dengan maksud untuk mengembangkan tema ini sebagai konflik utama cerita, tetapi sebaliknya sebagai bahan permenungan bagi penonton.
Saya sebetulnya menanti dialog yang lebih mendalam. Pada beberapa bagian sudah terdapat sinisme yang karikatural. Sebagai contoh, Intan mengatakan mereka sering dibebaskan dari karcis masuk pantai Krokowolon karena mereka adalah anak-anak misdinar. Ironi semacam ini menarik karena kampanye anti KKN dan transparansi yang sering dikotbahkan di mimbar gereja kini bisa dibobol oleh negosiasi “orang dalam”. Kekuatan sastra, termasuk sebuah teks pertunjukan terletak juga pada kemampuannya mengelaborasi elemen-elemen ironis dalam realitas. Namun, sekali lagi, karena formatnya berupa sharing pengalaman maka kisah-kisahnya terpenggal seperti potongan video Tiktok yang mesti segera disapu ke kiri dengan telunjuk. Tetapi okelah, hal ini tentu bisa diterima sebagai risiko dari format pertunjukan yang dipilih.
Sebagai anak Bali Angga pun merekam pengalaman senada. Ada ruang hidup warga yang perlahan-lahan direbut oleh pasar. “Ada salah satu pantai di kawasan Jimbaran, tepatnya di kecamatan Kuta selatan. Pantai Madu namanya. Letaknya di antara pantai Kelan dan Bandara. Sangat jelas perubahan suasana di sana. Dulunya jarang ada yang mengunjungi pantai itu baik turis lokal maupun asing, tapi sekarang sudah ramai sekali. Bahkan, sudah banyak restoran dan coffee shop.”
Ketika Intan dan Angga ditanya “Apa saja yang kamu lihat di pantai saat piknik?”, terdapat tiga kata kunci yang beririsan dalam jawaban mereka. “Laut”, “turis” dan “pedagang”.
Dibaca dari dari konteks sosial-politik lokal Maumere, adegan fragmen pertama ini merupakan proyeksi dari perebutan ruang publik oleh para pemilik modal yang diwakili oleh Gereja dan Pintu Air. Andaikata terjadi sengketa lahan antara keduanya boleh dipastikan pemilik modal bakal menang. Mereka mempunyai semua sumber daya yang dibutuhkan untuk membela diri di hadapan hukum. Konon, hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Namun, kekalahan warga di meja hijau, ancaman borgol dan jeruji penjara sekalipun tidak membungkam suara mereka. Perlawanan akar rumput bisa muncul di mana-mana sekalipun sporadis sifatnya. Silvy – pendorong gerobak yang menjual jajanan es kulkul – terus berteriak sendirian: “Fuck kapitalisme!” di sela-sela percakapan Intan, Angga, Gee dan Mags.
Satu pesan penting ditinggalkan dari pertunjukan Setali Cahaya malam itu. Perlawanan terhadap kekuasaan bisa sangat absurd. Ia berpotensi menjadi kebencian yang fanatik dan pada titik tertentu membabi-buta terhadap semua yang berjubah agama. Ketika ditanya ciri-ciri mantan pacaranya, dengan enteng Intan menjawab, “Manis, tinggi, dingin, penyayang, punya suara yang bagus dan yang penting bukan eks frater!”
Bagaimanapun juga konflik perebutan lahan meninggalkan luka pada pihak yang kalah. Luka itu tidak mudah disembuhkan dan kebencian terhadap Gereja bisa muncul secara reaktif dan absurd. Perlawanan kepada Gereja dan kebencian buta terhadap semua yang dekat dengan jubah sebagai wakil simbolik dari Gereja mengarah pada sejenis fanatisme yang kalau pusarannya membesar barang kali akan disesali oleh Gereja sendiri di kemudian hari.
Intan dan Angga membacakan pesan dengan tempo sangat cepat. Suara mereka berkejar-kejaran sehingga tidak jelas lagi apa yang hendak disampaikan. Keriuhan suasana pantai dilengkapi hentakan lagu Florentina yang diputar dari balik layar. Gee berdiri dan sibuk mengatur parkiran untuk kendaraan yang masuk area piknik. Bunyi pluit terdengar di sela-sela dentuman musik. Seperti hingar-bingar musik dan suara Intan-Angga yang berkejar-kejaran, Gereja bisa bersembunyi di balik derasnya arus informasi yang datang bagai banjir bandang. Semua berita segera menjadi sampah dan ingatan publik yang pendek menyebabkan kita cepat lupa akan semua luka yang telah ditorehkan pada kulit warga.
Menyaksikan adegan ini saya bertanya, monumen luka macam apa yang bisa bertahan untuk mengenang memoria passionis para korban di tengah arus deras informasi ini? Apakah salib Yesus masih penting atau sudah kehilangan daya pagutnya?
Jejak kekuasaan dalam kata
Sebagaimana perlawanan akar rumput yang sporadis, subtil dan bahkan absurd, kekuasaan pun diam-diam merayap di dalam bahasa. Dimas Rajalewa menutup fragmen pertama dengan presentasi riset berjudul “Historiografi leksikon Waktu Luang-Mobilitas: Studi Kasus Kata ‘Piknik’, ‘Pesiar’, dan ‘Pariwisata’”.
 Gambar 3. Dimas Rajalewa sedang memberi presentasi hasil risetnya (Dok. pribadi Ve Nahak)
Gambar 3. Dimas Rajalewa sedang memberi presentasi hasil risetnya (Dok. pribadi Ve Nahak)
Kehadiran presentasi riset ilmiah di tengah pertunjukan teater, setidaknya bagiku, merupakan suatu percobaan yang menarik. Durasi presentasi sekitar 20 menit tidak membosankan. Lebih lagi, karena pembicaranya adalah seorang magister linguistik, saya sendiri merasa naik level sebagai “penonton yang berkelas”. Curiculum Vitae pembicara yang disebut di awal sesi menekankan tentang keseriusan bagian ini.
“Kata‑kata yang tampak sederhana, seperti ‘piknik’ atau ‘pesiar’, bisa membawa muatan ideologis dan relasi kuasa sangat kompleks,” kata Dimas dalam presentasinya. Menurutnya, kata “piknik” dan “pesiar” digunakan untuk membedakan dua kelas sosial. Kaum elite kolonial menggunakan kata “piknik”, sedangkan kaum bumiputra menggunakan kata “pesiar”. Opsi untuk menggunakan kata “pesiar” karena memiliki rujukan dari bahasa Melayu merupakan cara mempertegas pembedaan antara kaum bumiputra dan kolonial.
Jejak kekuasaan itu lebih jauh bisa dilacak dalam lema “pariwisata” yang merupakan sebuah neologisme dalam kosakata bahasa Indonesia. Lema ini baru terekam pada tahun 1953 dalam kamus yang disusun Poerwadarminta. Dalam penelitiannya, Dimas menemukan kolokasi yang menarik terkait kata “pariwisata”.
“Pariwisata sebagai leksikon digunakan dengan kesadaran yang tidak berorientasi pada manusia. Lima besar kolokasi kata pariwisata sejak tahun 1969 sampai kampanye wonderful Indonesia memperlihatkan bahwa pariwisata sejak awal dan hingga saat ini lebih berorientasi pada ‘devisa’, ‘industri’, ‘modal’, ‘sarana’, dan ‘pengembangan’. Tidak satupun leksikon soal manusia dan budaya berkolokasi dengan pariwisata dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah, padahal yang dijual oleh industri pariwisata saat ini justru manusia dan budaya Indonesia,” pungkas Dimas.
Di balik kenyataan pahit di atas, Dimas masih menemukan secercah harapan yang tersembunyi di dalam bahasa Sikka. Untuk orang Maumere, kata “piknik” selalu memiliki asosiasi dengan pantai. “Dalam bahasa Sikka ada ungkapan “pano ta reta ilin” yang artinya pergi kerja kebun dan “pano ta lau ne” yang artinya pergi ke pantai untuk tujuan beristirahat atau rekreasi. Karena itu, tidak heran jika asosiasi piknik yang merupakan bagian dari domain semantik waktu luang diasosiasikan dengan Pantai (ne).”
Walaupun piknik masih bukan sesuatu yang eksklusif, yang hanya bisa diakses oleh kelompok elite tertentu saja, ancamannya di masa depan perlu diwaspadai. Okupasi pantai dengan dalih pariwisata religius atau pariwisata berkelanjutan bisa saja menghadirkan kembali piknik a la masa kolonial.
Hentakan lagu Ikan Nae di Pantai karya Alfred Gare, dkk menutup presentasi Dimas. Pilihan lagu Maumere yang viral di Youtube tahun 2024 lalu menggarisbawahi apa yang dikatakan Dimas dalam presentasinya: “Tubuh dan bahasa orang Maumere adalah tubuh dan bahasa pantai”.
Presentasi Dimas menunjukkan keseriusan Komunitas Kahe dan Aghumi untuk menyajikan teater yang berkualitas kepada penonton. Namun, kemasan pertunjukan ini mengandaikan lapisan penonton yang lebih beragam. Andaikata akan dibawakan lagi, mereka mesti bekerja ekstra keras untuk memobilisasi penonton dari kalangan pemerintah, gereja dan tokoh-tokoh masyarakat. Saya melihat, promosi pertunjukan ini sudah dibuat cukup masif baik lewat media sosial maupun lewat flyer yang dicetak, namun animo penonton masih rendah.
Kahe dan Aghumi sendiri menyadari pentingnya kehadiran penonton dan sumbangannya untuk memantik diskursus publik. Sesudah pertunjukan misalnya, para penonton sekali lagi diundang untuk berdiskusi dalam sesi yang diberi nama “Majelis Pertunjukan”. Di sana kami diminta memberikan kritik dan saran untuk pengembangan teater ini.
Cahaya putih di Liang Bua
Berbeda dari fragmen pertama yang menampilkan pengalaman sehari-hari, fragmen kedua menampilkan pengalaman riset yang lebih serius. Gee mengisahkan pengalamannya di Liang Bua-Flores, sedangkan Wulan berkisah tentang pengalamannya di Pura Pucak Petali-Bali. Di layar tertulis “Fragmen kedua: Pohon jambu air, sebuah jalan, rumah”.
Walaupun berangkat dari motif awal yang berbeda, kedua anak muda yang menjadi tokoh utama kali ini sama-sama menggali kekayaan budaya masa lalu. Wulan menyepi dari riuh pariwisata di kotanya dan mengakrabi elemen mistik sebuah arca macan dari abad 13, sedangkan Gee mengalami suasana di Liang Bua, tempat penggalian Homo floresiensis.
 Gambar 4. Dialog Gee dan Wulan (Dok. pribadi Ve Nahak)
Gambar 4. Dialog Gee dan Wulan (Dok. pribadi Ve Nahak)
Sama dengan fragmen pertama, bagian ini mudah diikuti karena dikemas dalam bentuk dialog. Dari percakapan mereka saya mencatat beberapa hal menarik.
Gee misalnya, merekam kisah menarik seorang ibu di Liang Bua. “Katanya, ada cahaya putih yang akan keluar dari Liang Bua pindah ke gua yang lain kalau ada periset yang datang, dan baru akan kembali ke tempatnya setelah para periset kembali.”
Di benakku muncul pertanyaan, apakah kisah semacam ini hanyalah keyakinan polos warga lokal Liang Bua yang masih percaya pada dongeng-dongeng mitis magis? Ataukah mesti ada cara lain untuk membaca narasi semacam ini?
Mitos-mitos seperti ini, dalam pandanganku, mengandung jejak resistensi masyarakat lokal. Orang-orang kampung tidak melawan secara frontal, tetapi sebaliknya dengan narasi-narasi kecil dan bersifat sporadis. Naluri untuk bertahan dari gempuran ilmu pengetahuan dan teknologi di bawah panji “riset” dilawan dengan narasi yang menegaskan kekuatan supranatural yang tidak bisa diakses oleh pengalaman empirik a la Barat.
Tampak bahwa terjadi pertarungan antara dua otoritas. Pada satu sisi terdapat otoritas ilmu pengetahuan yang diwakili oleh para periset dan di sisi lain otoritas pengetahuan lokal. Kalau para periset datang dari Barat dan melalui ekskavasi berusaha menyingkapkan misteri di balik lapisan-lapisan tanah, warga lokal mempunyai sejenis “pengalaman empirik” untuk mengakses benda-benda langit.
Apakah cahaya putih yang berpindah dari Liang Bua ke gua yang lain merupakan pratanda bahwa kesakralan elemen-elemen kosmik di Liang Bua mencari jalan lain untuk menghindari pencaplokan para periset yang mewakili superioritas Barat? Cahaya putih baru kembali sesudah para periset pergi.
Di layar tampak gambar-gambar dari arsip tua tentang misi Katolik di Flores. Gee menekankan peran penting Pastor Verhoeven dalam ekskavasi di Liang Bua, penemuan fosil stegodon dan koreksi terhadap teori Wallace-Line. Sepak terjang uskup Van Bekkum dari daerah misi Flores berkontribusi besar bagi konsep inkulturasi gereja. “Kita lihat kalau tradisi kita itu bukan sesuatu yang salah, tidak beradab, tetapi ada religiusitasnya juga.”
Inkulturasi bukan hanya soal perubahan kultus liturgi. Yang lebih esensial ialah sikap baru dalam bermisi untuk menghargai eksistensi kebudayaan-kebudayaan lokal dan masyarakat yang bernafas, hidup dan menghayati praktik-praktik budaya tersebut.
Kerja-kerja kebudayaan yang dirintis Verhoeven dan uskup Van Bekkum turut menyumbang perubahan paradigma Gereja dalam Konsili Vatikan II yang legendaris itu. Tentu terasa ironis ketika 60 tahun pasca konsili ekumenis tersebut, Gereja lokal di Maumere misalnya, tampak kembali hendak memberangus masyarakat adat. Apa yang terjadi di Maumere belakangan ini dalam kasus tanah Nangahale memantulkan kembali kisah si Ibu dari Liang Bua di atas. Cahaya putih sedang bergerak menjauh ke gua yang lain ketika wajah-wajah kolonial mendekat.
Perang tanding untuk “merebut lahan” ini seumpama kisah Wulan dalam perjalanannya ke Pura Pucak Petali. Ketika melewati area Desa Wisata Jatiluwih yang cantik mereka hendak menikmati pemandangan, namun tiba-tiba bus-bus pariwisata terparkir di depan mereka. Pemandangan terasering sawah mesti rela ditukar dengan tembok tinggi bus pariwisata. Jalan sempit, bunyi klakson dan macet menambah runyam suasana. Di Desa Jatiluwih, pengunjung hampir 1.500 setiap hari.
Pariwisata Bali ternyata tidak tampa masalah. “Di Bali sudah banyak kasus skizofrenia, bipolar, hingga bunuh diri terutama di kalangan usia produktif,” kata Wulan. Pariwisata ternyata mengandaikan pula ketahanan mental masyarakatnya. “Orang datang ke Bali untuk mencari kedamaian, tapi orang Bali sendiri kehilangan kedamaian itu,” ungkap Wulan. Namun, syukurlah karena di Pura Pucak Petali Wulan masih bisa menemukan kedamaian yang dirindukannya dan mungkin banyak orang Bali lain.
Pariwisata sebagai medan perjumpaan antara modernitas dan lokalitas menimbulkan kegelisahan yang diwakili dua anak milenial di atas panggung. Gee merefleksikan tiga isu penting. Pertama, soal absennya produk pengetahuan lokal. Metanarasi yang diproduksi di level global dan nasional memenuhi ruang-ruang pengetahuan kita, sedangkan pengetahuan lokal kita belum mendapat tempat. Kedua, soal siapa yang berkuasa dan mempunyai akses atas pengetahuan lokal itu?, Ketiga, soal urgensi memproduksi pengetahuan baru dari perspektif masyarakat lokal.
Fragmen kedua ditutup dengan permainan tarot. Wulan mengundang penonton, seorang gadis berbaju biru dari baris depan. Ia mengajaknya bercerita, mengocok kartu seperti pesulap profesional dan coba meramal masa depan.
 Gambar 5. Wulan sedang berinteraksi dengan salah satu penonton sambil memainkan kartu tarot (Dok. pribadi Ve Nahak)
Gambar 5. Wulan sedang berinteraksi dengan salah satu penonton sambil memainkan kartu tarot (Dok. pribadi Ve Nahak)
Permainan tarot menggarisbawahi pertanyaan: apakah kita mempunyai pilihan di masa depan? Ataukah, sebetulnya apa yang hari-hari ini disebut pilihan hanyalah opsi yang digiring oleh kepentingan pasar global?
Judul fragmen ketiga tertera di layar: “Seperti Mencari Jejak Burung Terbang”. Megs dan Angga masuk panggung. Keduanya bertelanjang dada, berdiri di sisi kiri dan kanan. Kedua anak muda itu saling menatap seperti sepasang musuh bebuyutan yang berdiri di kutup-kutup yang berlawanan. Keduanya mengepalkan tangan seperti sedang mengumpulkan tenaga dalam. Sesudah beberapa detik saling menatap mereka berlari seperti dua banteng di atas gelanggang yang hendak saling menanduk. Mereka mengadu kekuatan, berputar-putar searah jarum jam dan dengan ritme pelan kembali melangkah ke titik semula. Dari pengeras suara terdengar rekaman esai Anibal Qijano.
Di titik itu mereka mengatur nafas, mengepalkan tinju, saling menatap, dibakar sejenis amarah aneh, lalu berlari ke tengah panggung dan saling serunduk. Tarian itu berulang beberapa kali. Sorot lampu dari atas memantulkan keringat di tubuh Megs dan Angga. Adegan itu dilakukan seperti dua pegulat profesional yang sedang beradu kekuatan tanpa pitingan. Karena adegan terus berulang dengan ritme yang makin cepat, saya membayangkan bahwa salah satu dari mereka akan terguling kalah. Namun, adegan ini berakhir dengan cara yang berbeda. Keduanya tegak berdiri di posisi semula. Adegan ini, barang kali, hendak meninggalkan pesan bahwa pergulatan antara modernitas dan lokalitas tidak harus berakhir tragis.
Sesudah adegan itu, Intan, Silvy, dan Gee masuk ke panggung. Mereka berdiri di tiga titik membentuk segitiga siku-siku dan mulai menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan seseorang dari balik layar.
Suara seperti robot membaca pertanyaan yang muncul di latar panggung. “Menurutmu, di mana tempat ideal untuk bercinta?, Apa alasan kamu harus menikah?, Apa hal yang membuat kamu bahagia sekaligus kecewa?” Para pelakon menjawab sesuai versi masing-masing. Penonton pun sebenarnya sudah disiapkan sejak awal untuk masuk dalam adegan ini. Ketika menanti pementasan mulai, panitia menyodorkan daftar hadir yang dilengkapi dengan 3 pertanyaan yang mirip.
Di tengah percakapan muncul pula protes-protes kecil dari Intan dan Gee yang seolah merefleksikan sayup-sayup suara protes warga di tengah gempuran kemajuan. Ketakberdayaan warga ibarat pengalaman masa kecil Gee yang mesti kehilangan pohon jambu air kesayangan karena ada proyek pembangunan jalan yang melintas di kompleks rumahnya. “Saya lantas bertanya kepada bapak saya: bisakah jalan dibuat berbelok tanpa harus menebang pohon jambu air?”. Protes seperti ini kedengaran sangat puitik di tengah bisingnya pembangunan. Sukacita masa kanak-anak sama sekali tidak masuk dalam radar alat berat.
Deretan pertanyaan yang muncul dari pengeras suara ditimpali dengan beragam jawaban. Hanya ada satu pertanyaan yang dijawab seragam. “Mengapa ada orang-orang di sekitar kamu yang kaya raya?” Semua menjawab: “Kapitalisme!” Jawaban itu diteriakkan bergilir. Suara para pelakon terdengar sahut-menyahut seperti protes yang menggebu-gebu memecah kesunyian.
Ketiganya berlari berputar mengitari panggung tiga kali. Silvy kemudian tampil membacakan kisah pergulatan hidupnya. Sampai di sini, pertarungan modernitas dan lokalitas yang diperankan Mags dan Angga di atas panggung pada adegan sebelunya seolah menemukan medan tempur yang lebih sengit di dalam tubuhnya sendiri. Andreas Sudirman Moa Laju dan Silvy Chipy ibarat dua sosok yang bergulat untuk merebut tubuh yang sama.
Tubuh yang pernah ditindas oleh adat, budaya dan agama telah memproklamasikan dirinya sebagai republik yang merdeka. Penjajah telah diusir dan bendera kemenangan telah dikibarkan. Ia kini berdaulat sebagai mawar yang cantik (Dala Mawarani) di dalam tubuhnya sendiri.